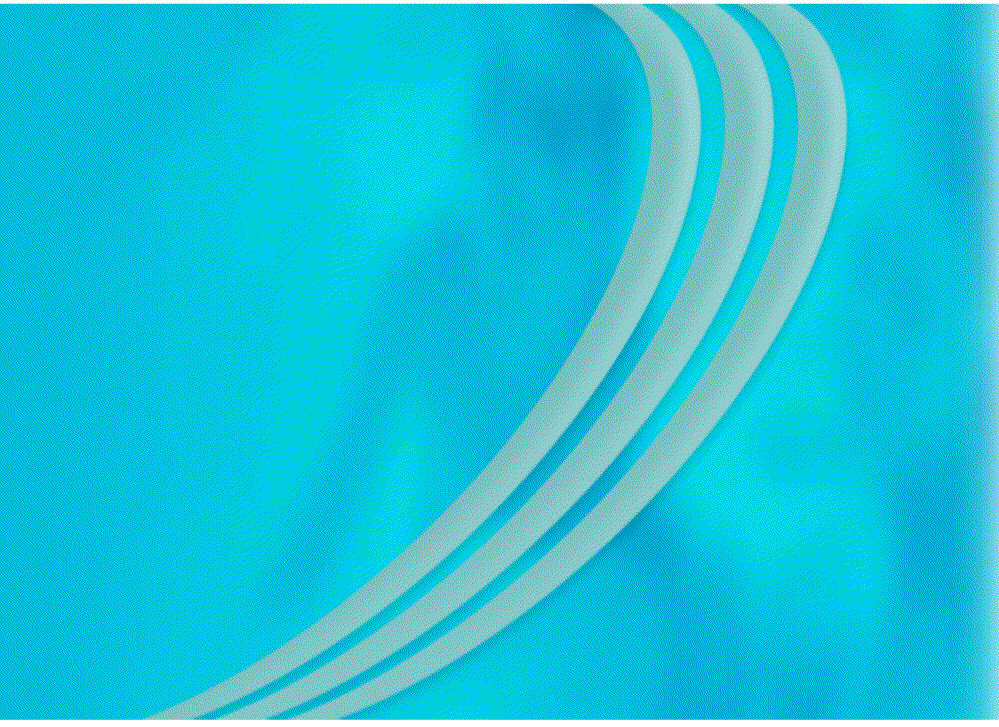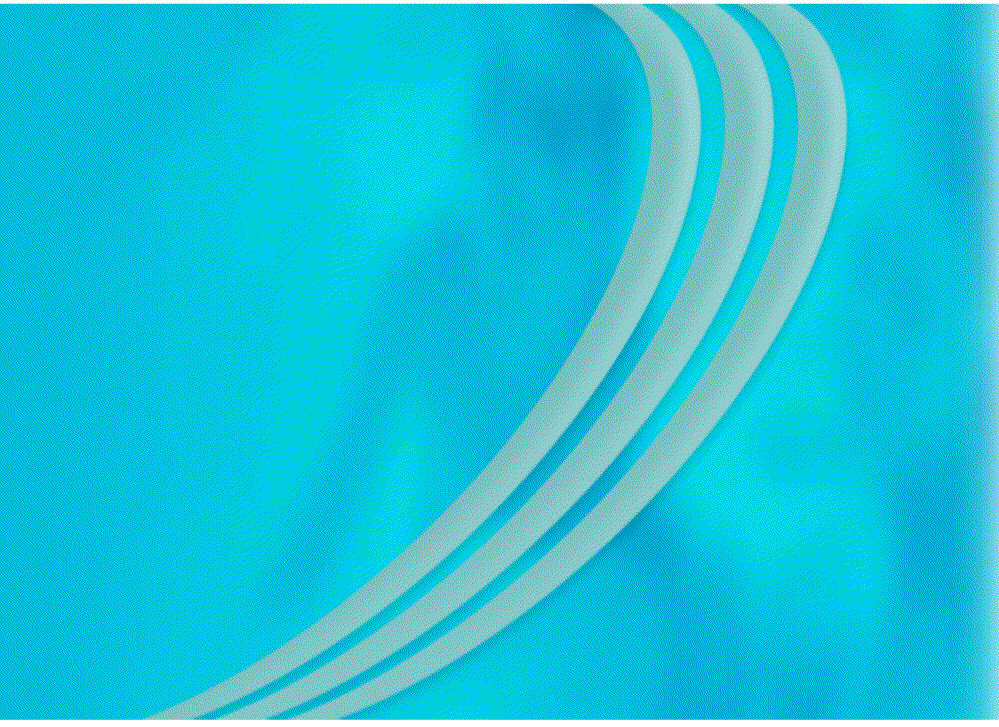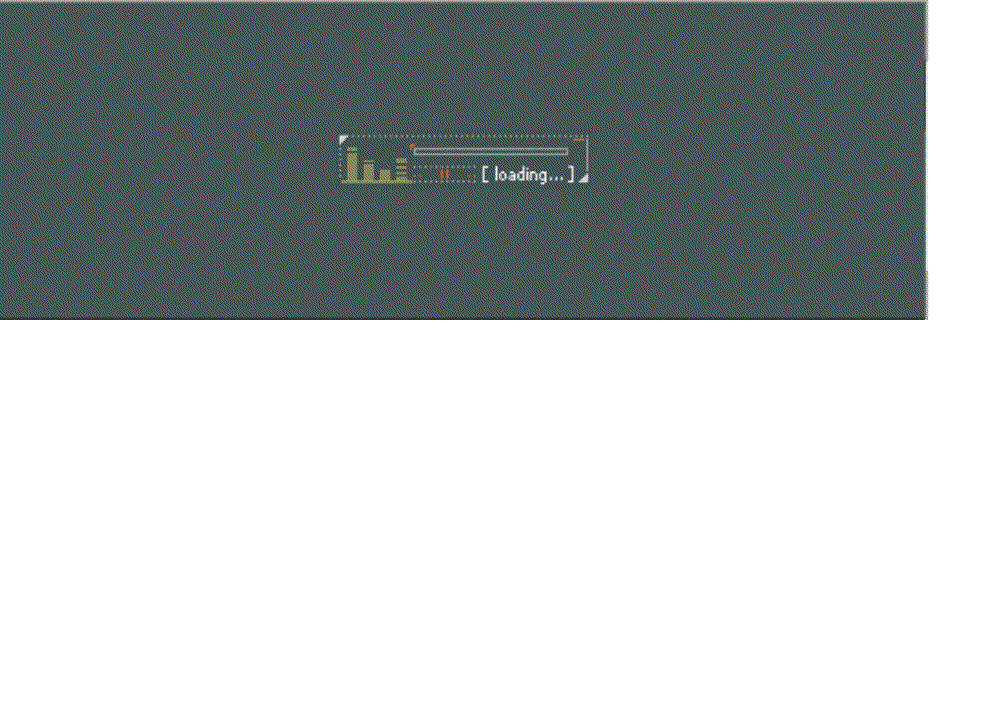Contoh:
Pada saat matahari mencapai garis balik utara (tropic of Cancer),
kira-kira pada tanggal 21 Juni, belahan bumi selatan mengalami musim
dingin, dan pada saat matahari mencapai garis balik selatan (tropic of
Capicorn), kira-kira tanggal 22 Desember, bumi belahan utara mengalami
musim dingin. Contoh kalender matahari adalah kalender Gregorian.
Sedangkan kalender bulan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi.
Waktu yang diperlukan untuk satu kali revolusi adalah satu bulan kalender
bulan, kira-kira 29 1/2 hari. Contoh kalender bulan adalah kalender
Hijriyah dan kalender Jawa.
Bangsa Tionghua mengenal kalender matahari (Yangli[Yonglek/Yanglek]) dan
kalender bulan (Yinli [Yimlek]). Kalender matahari terdiri 24 jieqi [cuekhui]
(musim matahari) yaitu:
No. Nama Musim Tanggal Kld. Gregorian
1. lichun [lipchun] 4,5 Februari
2. yushui [wusui] 18,19 Februari
3. jingzhe [kingtip] 5,6 Maret
4. chunfen [chunhun] 20,21 Maret
5. qingming [chni'mia/chingbing] 4,5 Apr
6. guyu [kokwu] 19,20 April
7. lixia [liphe] 5,6 Mei
8. xiaoman [siaobuan] 21,22 Mei
9. mangzhong [bongcing] 5,6 Juni
10. xiazhi [heci] 21,22 Juni
11. xiaoshu [siaosu] 7,8 Juli
12. daxhu [taisu] 22,23 Juli
13. liqiu [lipchiu] 7,8 Agustus
14. chushu [chusu] 23 Agustus
15. bailu [peklo] 7,8 September
16. qiufen [chiuhun] 22,23 September
17. hanlu [hanlo] 8,9 Oktober
18. shuangjiang [sngkang] 23,24 Oktober
19. lidong [liptang] 7,8 November
20. xiaoxue [siaosuat] 22,23 November
21. daxue [taisuat] 7,8 Desember
22. dongzhi [tangci/tangcue] 21,22 Desember
23. xiaohan [siaohan] 5,6 Januari
24. dahan [taihan] 20,21 Januari
catatan:
1. 24 jieqi ini sebenarnya terdiri atas 12 bulan tahun matahari, urutan
ganjil (lichun, jingzhe, dst...) adalah awal bulan, urutan genap (yushui,
chunfen, dst...) adalah tengah bulan.
2. Jieqi yang paling sering dirayakan di Indonesia adalah [chingbing] (ziarah
ke makam leluhur) dan [tangcue] (memakan ronde [yni'a thng]).
3. Coba diperhatikan persamaan tanggal tengah bulan dengan tanggal
horoskop barat.
Sedangkan kalender bulan terdiri dari 12 bulan, ada bulan besar 30 hari
dan bulan kecil 29 hari. Satu tahun terdiri dari 12 bulan sehingga jumlah
hari pertahun adalah 354 hari. Karena jumlah tahun matahari kira-kira 365
1/4 hari, maka akan ada selisih sebesar 11 1/4 hari pertahun. Untuk
menyesuaikan kalender dengan kalender Yangli, ditambahkan bulan kabisat
runyue [lun'ge]. Sehingga satu tahun terdiri dari 13 bulan. Penambahan
bulan kabisat ini dilakukan 7 kali dalam 19 tahun.
Jadi, sistem kalender Tionghua adalah kombinasi antara kalender bulan dan
kalender matahari (kalender lunisolar).
KOMBINASI TIANGAN DIZHI
Semua komponen waktu (jam, hari, bulan, tahun) adalah kombinasi dari 10
tiangan [thiankan] (batang langit) dan 12 dizhi [teci] (cabang bumi). Jadi,
untuk setiap komponen ada 60 kombinasi. Berikut ini adalah urutan tiangan
dan dizhi:
No. tiangan unsur
1 jia [ka] kayu
2 yi [yit] kayu
3 bing [pnia] api
4 ding [ting] api
5 wu [mo] tanah
6 yi [ki] tanah
7 geng [king] logam
8 xin [sin] logam
9 ren [jim] air
10 gui [kui] air
No. dizhi unsur xiao [snio] jam
1 zi [cu] air tikus 23 - 01
2 chou [thiu] tanah sapi 01 - 03
3 yin [yin] kayu macan 03 - 05
4 mao [bao] kayu kelinci 05 - 07
5 chen [sin] tanah naga 07 - 09
6 si [su] api ular 09 - 11
7 wu [ngo] api kuda 11 - 13
8 wei [bi] tanah kambing 13 - 15
9 shen [sin] logam monyet 15 - 17
10 you [yu] logam ayam 17 - 19
11 xu [sut] tanah anjing 19 - 21
12 hai [hai] air babi 21 - 23
Setiap tahun (juga bulan, hari, dan jam) adalah kombinasi dari tiangan dan
dizhi. Jadi kalau hari ini adalah hari jiazi, besok adalah hari yichou,
kemarin adalah hari guihai.
CAP JI SNIO
Horoskop Tionghua [cap ji snio] yang dikenal oleh banyak orang adalah
kombinasi tiangan dan dizhi pada komponen tahun. Sebagai contoh: tahun ini
adalah tahun xinsi, yang disebut tahun ular logam, tahun lalu adalah tahun
gengchen = naga logam, tahun depan adalah tahun renwu = kuda api.
Sesungguhnya perhitungan peruntungan seseorang, kuranglah lengkap jika
hanya melihat dari snio-nya saja. Karena, snio adalah salah satu dari
empat komponen kelahiran seseorang. Jadi, kita harus memperhitungkan
kombinasi tiangan-dizhi dari tahun, bulan, hari, dan jam kelahiran
seseorang. Selanjutnya, akan diperoleh 4 pasang kombinasi dari komponen
tahun, bulan, hari, dan jam kelahirannya, yang bisa dianalisis peruntungan
orang tsb. Empat pasang kombinasi tiangan-dizhi ini disebut bazi [pueji] (delapan
huruf).
Selama ini banyak orang menganggap bahwa horoskop Tionghua 'hanya'
mengenal 60 kombinasi (berdasarkan tahun kelahiran saja). Sesungguhnya
setiap komponen kelahiran (tahun, bulan, hari, jam) mempunyai 60 kombinasi.,
sehingga total ada 60 x 60 x 60 x 60 = 12.960.000 kombinasi yang berbeda.
catatan:
seluruh istilah bahasa Tionghoa menggunakan dialek Mandarin dengan ejaan
Hanyupinyin serta dialek [Hokkian].
Serba-serbi Cap-Go-Meh
Cap-Go-Meh adalah lafal dialek Tio Ciu dan Hokkian. Artinya malam 15.
sedangkan lafal dialek Hakka Cang Njiat Pan. Artinya pertengahan bulan
satu. Di daratan Tiongkok dinamakan Yuan Xiau Jie dalam bahasa Mandarin
artinya festival malam bulan satu. Capgome mulai dirayakan di Indonesia
sejak abad ke 17, ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan.
Semasa dinasti Han, pada malam capgome tersebut, raja sendiri khusus
keluar istana untuk turut merayakan bersama dengan rakyatnya.
Setiap hari raya baik religius maupun tradisi budaya ada asal- usulnya.
Pada saat dinasti Zhou (770 - 256 SM) setiap tanggal 15 malam bulan satu
Imlek para petani memasang lampion-lampion yang dinamakan Chau Tian Can
di sekeliling ladang untuk mengusir hama dan menakuti binatang-binatang
perusak tanaman. Memasang lampion-lampion selain bermanfaat mengusir
hama, kini tercipta pemandangan yang indah dimalam hari tanggal 15 bulan
satu. Dan untuk menakuti atau mengusir binatang-binatang perusak tanaman,
mereka menambah segala bunyi-bunyian serta bermain barongsai, agar lebih
ramai dan bermanfaat bagi petani. Kepercayaan dan tradisi budaya ini
berlanjut turun menurun, baik didaratan Tiongkok maupun diperantauan
diseluruh dunia. Ini adalah salah satu versi darimana asal muasalnya
Capgome.
Di barat Capgome dinilai sebagai pesta karnevalnya etnis Tionghoa,
karena adanya pawai yang pada umumnya dimulai dari Kelenteng. Kelenteng
adalah penyebutan secara keseluruhan untuk tempat ibadah “Tri Dharma”
(Buddhism , Taoism dan Confuciusm). Nama Kelenteng sekarang ini sudah
dirubah menjadi Vihara yang sebenarnya merupakan sebutan bagi rumah
ibadah agama Buddha. Hal ini terjadi sejak pemerintah tidak mengakui
keberadaannya agama Kong Hu Chu sebagai agama.
Sedangkan sebutan nama Kelenteng itu sendiri, bukannya berasal dari
bahasa China, melainkan berasal dari bahasa Jawa, yang diambil dari
perkataan “kelintingan” – lonceng kecil, karena bunyi-bunyian inilah
yang sering
keluar dari Kelenteng, sehingga mereka menamakannya Kelenteng. Orang
Tionghoa sendiri menamakan Kelenteng itu, sebagai Bio baca Miao. Wen
Miao adalah bio untuk menghormati Confucius dan Wu Miao adalah untuk
menghormati Guan Gong.
Cagomeh juga dikenal sebagai acara pawai menggotong joli Toapekong untuk
diarak keluar dari Kelenteng. Toapekong (Hakka = Taipakkung, Mandarin =
Dabogong) berarti secara harfiah eyang buyut untuk makna kiasan bagi
dewa yang pada umumnya merupakan seorang kakek yang udah tua. “Da Bo
Gong” ini sebenarnya adalah sebutan untuk para leluhur yang merantau
atau para pioner dalam mengembangkan komunitas Tionghoa. Jadi istilah Da
Bo Gong itu sendiri tidak dikenal di Tiongkok.
Cagomeh tanpa adanya barongsai dan liong (naga) rasanya tidaklah komplit.
Tarian barongsay atau tarian singa biasanya disebut “Nong Shi”.
Sedangkan nama “barongsai” adalah gabungan dari kata Barong dalam bahasa
Jawa dan Sai = Singa dalam bahasa dialek Hokkian. Singa menurut orang
Tionghoa ini melambangkan kebahagiaan dan kegembiraan.
Ada dua macam jenis macam tarian barongsay yang satu lebih dikenal
sebagai Singa Utara yang penampilannya lebih natural sebab tanpa tanduk,
sedangkan Singa Selatan memiliki tanduk dan sisik jadi mirip dengan
binatang Qilin (kuda naga yang bertanduk).
Seperti layaknya binatang-binatang lainnya juga, maka barongsai juga
harus diberi makan berupa Angpau yang ditempeli dengan sayuran selada
air yang lazim disebut “Lay See”. Untuk melakukan tarian makan laysee (Chai
Qing) ini para pemain harus mampu melakukan loncatan tinggi, sehingga
ketika dahulu para pemain barongsai, hanya dimainkan oleh orang-orang
yang memiliki kemampuan silat – “Hokkian = kun tao” yang berasal dari
bahasa Mandarin Quan Dao (Kepala kepalan atau tinju), tetapi sekarang
lebih dikenal dengan kata Wu Shu, padahal artinya Wu Shu sendiri itu
adalah seni menghentikan kekerasan.
Didepan barongsai selalu terdapat seorang penari lainnya yang
menggunakan topeng sambil membawa kipas. Biasanya disebut Shi Zi Lang
dan penari inilah yang menggiring barongsai untuk meloncat atau bermain
atraksi serta memetik sayuran. Sedangkan penari dengan topeng Buddha
tertawa disebut Xiao Mian Fo.
Pada awalnya tarian barongsai ini tidak pernah dikaitkan dengan ritual
keagamaan manapun juga, tetapi akhirnya karena rakyat percaya, bahwa
barongsai itu dapat mengusir hawa-hawa buruk dan roh-roh jahat. Jadi
budaya atau kepercayaan rakyat itulah yang akhirnya dimanfaatkan atau
bersinergi dengan lembaga keagamaan.
Walaupun demikian pada saat sekarang ini sudah ada aliran modern lainnya
yang tidak mengkaitkan dengan upacara keagamaan sama sekali, karena
mereka menilai barongsai hanya sekedar asesories untuk nari atau media
entertainment saja, seperti juga halnya dengan payung untuk tari payung,
atau topeng dalam tarian topeng.
Barongsai sebenarnya sudah populer sejak zaman periode tiga kerajaan
(Wu, Wei & Shu Han) tahun 220 – 280 M.
Pada saat itu ketika raja Song Wen sedang kewalahan menghadapi serangan
pasukan gajah Raja Fan Yang dari negeri Lin Yi. Panglimanya yang bernama
Zhing Que mempunyai ide yang jenius dengan membuat boneka-boneka singa
tiruan untuk mengusir pasukan raja Fan. Ternyata usahanya itu berhasil
sehingga sejak saat ini mulailah melegenda tarian barongsai tersebut
hingga kini.
Tarian naga (liong) disebut “Nong Long”. Binatang mitologi ini selalu
digambarkan memiliki kepala unta, bertaring serigala dan bertanduk
menjangan.
Naga di Cina dianggap sebagai dewa pelindung, yang bisa memberikan
rejeki, kekuatan, kesuburan dan juga air. Air di Cina merupakan lambang
rejeki, karena kebanyakan dari mereka hidup dari bercocok tanam, maka
dari itu mereka sangat menggantungkan hidupnya dari air. Semua kaisar di
Cina menggunakan lambang naga, maka dari itu mereka duduk di singgasana
naga, tempat tidur naga, dan memakai pakaian kemahkotaan naga. Orang
Cina akan merasa bahagia apabila mendapatkan seorang putera yang lahir
di tahun naga.
Kita bisa melihat apakah ini naga lambang dari seorang kaisar ataukah
bukan dari jumlah jari di cakarnya. Hanya kaisar yang boleh menggunakan
gambar naga dengan lima jari di cakarnya, sedangkan untuk para pejabat
lainnya hanya 4 jari. Bagi rakyat biasa yang menggunakan lambang naga
cakarnya hanya boleh memiliki 3 jari saja. Naga itu memiliki tiga macam
warna, hijau, biru dan merah, dari warna naga tersebut kita bisa melihat
kesaktiannya. Naga warna kuning adalah naga yang melambangkan raja.
Pada umumnya untuk tarian naga ini dibuatkan naga yang panjangnya
sekitar 35 m dan dibagi dalam 9 bagian, tetapi ketika mereka menyambut
tahun baru millennium di China pernah dibuat naga yang panjangnya 3.500
meter dan dimainkannya di atas Tembok Besar China.
Naga tidak selalu dihormati, sebab apabila ada musim kemarau
berkepanjangan, maka para petani mengadakan upacara menjemur naga yang
dibuat dari tanah liat untuk membalas dendam atau mendemo sang Naga yang
tidak mau menurukan hujan, seakan-akan kaum tani tersebut ingin
menyatakan “Rasain Lho kering dan panasnya musim kemarau ini!”
Terutama di Jkt dan sekitarnya rasanya kurang komplit apabila pawai
Capgome ini tanpa di iringi oleh para pemain musik „Tanjidor“ yang
menggunakan instrument musik trompet, tambur dan bajidor (Bedug). Orkes
ini sudah dikenal sejak abad ke 18. Konon Valckenier gubenur Belanda
pada saat itu sudah memiliki rombongan orkes tanjidor yang terdiri dari
15 orang pemain musik. Tanjidor biasanya hanya dimainkan oleh para
budak-budak, oleh sebab itulah musik Tanjidor ini juga sering disebut
sebagai „Sklaven Orkest“.
ADAT KEMATIAN
ADAT KEMATIAN Kita sering melihat upacara kematian
Suku Tionghoa di tempat-tempat / ruang duka di rumah-rumah sakit.
Kelihatannya begitu ramai oleh aneka perhiasan rumah-rumahan dengan
perlengkapannya dan upacara yang bising serta pakaian duka cita yang
dipakai oleh anak, menantu dan cucu-cucunya.
Tetapi sebagian besar dari kita bertanya-tanya dan belum tahu apa arti
semua itu? Adat upacara kematian suku Tionghoa dilatarbelakangi oleh
kepercayaan mereka. Mereka mempercayai bahwa dalam relasi seseorang
dengan Tuhan atau kekuatan-kekuatan lain yang mengatur kehidupan baik
langsung maupun tidak langsung, berlaku hal-hal sebagai berikut : •
Adanya reinkarnasi bagi semua manusia yang telah meninggal (cut sie) •
Adanya hukum karma bagi semua perbuatan manusia, antara lain tidak
mendapat keturunan (ko kut) • Leluhur yang telah meninggal (arwah
leluhur) pada waktu-waktu tertentu dapat diminta datang untuk dijamu (Ce'ng
be'ng) • Menghormati para leluhur dan orang pandai (tuapekong) • Kutukan
para leluhur, melalui kuburan dan batu nisan yang dirusak (bompay) • Apa
yang dilakukan semasa hidup (di dunia) juga akan dialami di alam akhirat.
Kehidupan sesudah mati akan berlaku sama seperti kehidupan di dunia ini
namun dalam kualitas yang lebih baik. UPACARA-UPACARA YANG DILAKSANAKAN
DALAM KEMATIAN Upacara kematian terdiri atas empat tahap yaitu : A.
Belum masuk peti • Semenjak terjadinya kematian, anak-cucu sudah harus
membakar kertas perak (uang di akhirat ) merupakan lambang biaya
perjalanan ke akhirat yang dilakukan sambil mendoakan yang meninggal. •
Mayat dimandikan dan dibersihkan, lalu diberi pakaian tujuh lapis.
Lapisan pertama adalah pakaian putih sewaktu almarhum/almarhumah menikah.
Selanjutnya pakaian yang lain sebanyak enam lapis. • Sesudah dibaringkan;
kedua mata, lubang hidung, mulut, telinga, diberi mutiara sebagai
lambang penerangan untuk berjalan ke alam lain. • Di sisi kiri dan kanan
diisi dengan pakaian yang meninggal. Sepatu yang dipakai harus dari kain.
Apabila yang meninggal pakai kacamata maka kedua kaca harus dipecah yang
melambangkan bahwa dia telah berada di alam lain. B. Upacara masuk peti
dan penutupan peti • Seluruh keluarga harus menggunakan pakaian tertentu.
Anak laki-laki harus memakai pakaian dari blacu yang dibalik dan diberi
karung goni. Kepala diikat dengan sehelai kain blacu yang diberi
potongan goni. Demikian pula pakaian yang dipakai oleh anak perempuan
namun ditambah dengan kekojong yang berbentuk kerucut untuk menutupi
kepala. Cucu hanya memakai blacu, sedangkan keturunan ke empat memakai
pakaian berwarna biru. Keturunan ke lima dan seterusnya memakai pakaian
merah sebagai tanda sudah boleh lepas dari berkabung. • Mayat harus
diangkat oleh anak-anak lelaki almarhum. Sementara itu anak perempuan,
cucu dan seterusnya harus terus menangis dan membakar kertas perak, di
bawah peti mati. Mereka harus memperlihatkan rasa duka cita yang amat
dalam sebagai tanda bakti (uhaouw). Bila kurang banyak (tidak ada) yang
meratap, maka dapat menggaji seseorang untuk meratapi dengan bersuara,
khususnya pada saat tiba waktunya untuk memanggil makan siang dan makan
malam. • Sesudah masuk peti, ada upacara penutupan peti yang dipimpin
oleh hwee shio atau cayma. Bagi yang beragama Budha dipimpin oleh Biksu
atau Biksuni, sedangkan penganut Konfusius melakukan upacara Liam keng.
Upacara ini cukup lama, dilaksanakan di sekeliling peti mati dengan satu
syarat bahwa air mata peserta pada upacara penutupan peti tidak boleh
mengenai mayat. Dalam upacara ini juga dilakukan pemecahan sebuah kaca /
cermin yang kemudian dimasukkan ke dalam peti mati. Menurut kepercayaan
mereka, pada hari ke tujuh almarhum bangun dan akan melihat kaca
sehingga menyadarkan dia bahwa dirinya sudah meninggal. • Bagi anak cucu
yang "berada" (kaya), mulai menyiapkan rumah-rumahan yang diisi dengan
segala perabotan rumah tangga yang dipakai semasa hidup almarhum.
Semuanya harus dibuat dari kertas. Bahkan diperbolehkan diisi secara
berlebih-lebihan, termasuk adanya para pembantu rumah tangga. Semua
perlengkapan ini dapat dibeli pada toko tertentu. • Setiap tamu-tamu
yang datang harus di sungkem (di soja) oleh anak-anaknya, khusus anak
laki-laki. • Di atas meja kecil yang terletak di depan peti mati, selalu
disediakan makanan yang menjadi kesukaan semasa almarhum masih hidup. •
Upacara ini berlangsung berhari-hari. Paling cepat 3 atau 4 hari. Makin
lama biasanya makin baik. Dilihat juga hari baik untuk pemakaman. •
Selama peti mati masih di dalam rumah, harus ada sepasang lampion putih
yang selalu menyala di depan rumah. Hal ini menandakan bahwa ada orang
yang meninggal di rumah tersebut. C. Upacara pemakaman • Menjelang peti
akan diangkat, diadakan penghormatan terakhir. Dengan dipimpin oleh hwee
shio atau cayma, kembali mereka melakukan upacara penghormatan. •
Sesudah menyembah (soja) dan berlutut (kui), mereka harus mengitari peti
mati beberapa kali dengan jalan jongkok sambil terus menangis; mengikuti
hwee shio yang mendoakan arwah almarhum. • Untuk orang kaya, diadakan
meja persembahan yang memanjang ?2 sampai 5 meter. Di atas meja
disediakan macam-macam jenis makanan dan buah-buahan. Pada bagian depan
meja diletakkan kepala babi dan di depan meja berikutnya kepala kambing.
Makanan yang harus ada pada setiap upacara kematian adalah "sam seng",
yang terdiri dari lapisan daging dan minyak babi (Samcan), seekor ayam
yang sudah dikuliti, darah babi, telur bebek. Semuanya direbus dan
diletakkan dalam sebuah piring lonjong besar. • Putra tertua memegang
photo almarhum dan sebatang bambu yang diberi sepotong kertas putih yang
bertuliskan huruf Cina, biasa disebut "Hoe". Ia harus berjalan dekat
peti mati, diikuti oleh saudara-saudaranya yang lain. Begitu peti mati
diangkat, sebuah semangka dibanting hingga pecah sebagai tanda bahwa
kehidupan almarhum di dunia ini sudah selesai. • Dalam perjalanan menuju
tempat pemakaman, di setiap persimpangan, semua anak harus berlutut
menghadap orang-orang yang mengantar jenasah. Demikian pula setelah
selesai penguburan. • Setibanya di pemakaman, kembali diadakan upacara
penguburan. Memohon kepada dewa bumi ("toapekong" tanah) agar mau
menerima jenasah dan arwah almarhum, sambil membakar uang akhirat. •
Semua anak - cucu tidak diperkenankan meninggalkan kuburan sebelum
semuanya selesai, berarti peti sudah ditutup dengan tanah dalam bentuk
gundukan. Di atas gundukan diberi uang kertas perak yang ditindih dengan
batu kecil. Masing-masing dari mereka harus mengambil sekepal /
segenggam tanah kuburan dan menyimpannya di ujung kekojong. • Setibanya
di rumah, mereka harus membasuh muka dengan air kembang. Sekedar untuk
melupakan wajah almarhum. D. Upacara sesudah pemakaman • Semenjak ada
yang meninggal sampai saat tertentu, semua keluarga harus memakai
pakaian dan tanda berkabung terbuat dari sepotong blacu yang dilikatkan
di lengan atas kiri. Tidak boleh memakai pakaian berwarna ceria, seperti
: merah, kuning, coklat, oranye. • Waktu perkabungan berlainan lamanya,
tergantung siapa yang meninggal, • untuk kedua orangtua, terutama ayah
dilakukan selama 2 tahun. • untuk nenek dan kakek dilakukan selama 1
tahun. • untuk saudara dilakukan selama 3 atau 6 bulan. • Di rumah
disediakan meja pemujaan, rumah-rumahan dan tempat tidur almarhum.
Setiap hari harus dilayani makannya seperti semasa almarhum masih hidup.
• Upacara sesudah pemakaman biasanya terdiri dari : • Meniga hari (3
hari sesudah meninggal) Sesudah 3 hari meninggal seluruh keluarga
melakukan upacara penghomatan dan peringatan di tempat jenasah berada (pergi
ke kuburan almarhum). Mereka membawa makanan, buah-buahan, dupa, lilin,
uang akhirat. Dengan memakai pakaian berkabung/blacu mereka melakukan
upacara penghormatan (soja dan kui). Tak lupa mereka juga menangis dan
meratap sambil membakar uang akhirat. Pulang ke rumah, kembali mencuci
muka dengan air kembang. • Menujuh hari (7 hari sesudah meninggal)
Seperti halnya upacara meniga hari, seluruh keluarga melakukan upacara
penghomatan dan peringatan di tempat jenasah berada (kembali ke kuburan
). Mereka membawa rumah-rumahan, makanan dan buah-buahan serta uang
akhirat. Lilin dan dupa ( hio ) dinyalakan. Seluruh rumah-rumahan dan
sisa harta yang perlu dibakar; dibakar sambil melakukan upacara
mengelilingi api pembakaran. Sesudah selesai, tanah sekepal / segenggam
diambil, diserakkan ke atasnya. • 40 hari sesudah meninggal Pada hari ke
40 ini kembali anak - cucu dan keluarga melakukan upacara penghormatan
di tempat jenasah berada ( kuburan). Semua baju duka dari blacu dan
karung goni dibuka dan diganti baju biasa. Mereka masih dalam keadaan
berkabung, namun telah rela melepaskan arwah si almarhum ke alam akhirat.
Sebagai tanda tetap berkabung, semua anak cucu memakai tanda di lengan
kiri atas; berupa sepotong kain blacu dan goni. • Tiap-tiap tahun
memperingati hari kematian Satu tahun dan tahun-tahun berikutnya, akan
selalu diperingati oleh anak cucunya dengan melakukan " soja dan kui"
sebagai tanda berbakti dan menghormati. Peringatan tahunan ini berupa
upacara persembahan. Bagi keluarga yang berada, di atas meja persembahan
diletakkan berbagai macam makanan, buah-buahan, minuman, antara lain teh
dan kopi, manisan minimum 3 macam, rokok, sirih sekapur, sedangkan
makanan yang paling utama adalah "samseng" 2 pasang, lilin merah
sepasang dan hio. Senja hari sebelum upacara, harus dinyalakan lilin
merah berpasang-pasang tergantung pada jumlah orang / leluhur yang akan
diundang. Maksud dari upacara ini adalah meminta kepada dewa bumi (toapekong
tanah) untuk membukakan jalan bagi para arwah yaitu dengan cara membakar
uang akhirat (kertas perak dan kertas emas ). B. Ginarti K., Media Cetak